PENGEMBANGAN AJARAN AHLUSSUNNAH
WALJAMA’AH
DI ABAD 21
Diajukan
untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Aswaja
Dosen Pengampu :
Dr.
KH. Dahlan Thamrin, M.Ag
Oleh
:
MAKINUDDIN (2121030031)
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2012
PENGEMBANGAN AJARAN AHLUSSUNNAH
WALJAMA’AH
DI ABAD 21
Pemahaman Aswaja masuk ke Indonesia
bersamaan dengan masuknya Islam sekitar abad ke-3 Hijriyah atau abad 9 Masehi.
Menurut Prof. DR. Alwi Shihab dalam bukunya “Islam Sufistik”, orang-orang
Arab-lah pelopor pertama yang memperkenalkan Islam di kepulauan Nusantara,
yakni dari keturunan Imam Ahmad bin Isa Al Muhajir, kemudian dikembangkan oleh
para wali songo. Namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran-pergeseran
sesuai pergerakan waktu. Apalagi penganut atau pendukung-pendukung Aswaja
sendiri tidak banyak memahami perbedaan asasi dan perbedaan far’iy antara yang
Aswaja dan yang bukan. Pengertian aswaja selama ini masih belum banyak
dipahamii secara utuh oleh sebagian masyarakat bahkan warga NU sendiri, di
bidang fiqih mereka beranggapan bahwa aswaja hanya masalah qunut, tarawih,
adzan dua kali pada waktu jum’at,
Bahkan dikalangan pendukung
Madzahib al Arba’ah sendiri banyak yang tidak memahami, mana qaul yang masih
termasuk dalam lingkungan Madzahib al Arba’ah dan mana yang tidak termasuk. Hal
itu karena langkanya pengkajian tentang masalah Madzahib. Kadang-kadang
pendapat atau qaul Hanafiyah karena kebetulan berbeda dengan Syafi’iyah,
sudah dicap bukan Aswaja. sehingga memungkinkan adanya gesekan-gesekan antara
warga NU sendiri.
Dibidang tasawuf masih banyak orang
yang memahami bahwa tasawuf hanya berkisar pada amalan-amalan yang bersifat
ritual saja, semisal membaca wirid, berkholwat,(mengasingkan diri dari khalayak
ramai), mengikuti thoriqoh.
Dalam bidang akidah, mereka hanya
memahami rukun islam dan rukun iman saja belum banyak menyentuh pada akidah
yang mestinya dipahami oleh warga aswaja yakni akidah yang terkenal dengan
aqoid 50.
Tantangan semacam ini sekarang
lebih terasa lagi, setelah banyak generasi muda dan cendekiawan Aswaja mendapat
kesempatan mempelajari kitab-kitab fiqih dari berbagai macam aliran, baik
melalui kepustakaan maupun pendidikan formal, baik dalam negeri maupun di luar negeri.seperti
tentang konsep Modernisasi (fikrah al Tajaddud), yang ingin mengadakan
pembaharuan-pembaharuan dalam pemahaman, penafsiran dan perumusan
masalah-masalah keislaman, dengan pretensi ingin mengaktualisasikan Islam dalam
kehidupan modern. Issu yang paling getol dikemukakan adalah membuka kembali
pintu ijtihad selebar-lebarnya, dan penggunaan akal yang sebesar-besarnya.
Liberalisasi ijtihad ini menjadi
semakin parah, setelah menjalar kepada orang-orang yang tidak banyak mengerti
tentang agama, tapi berminat untuk ijtihad, sehingga ijtihad menjadi mode tanpa
standarisasi dan disiplin. Sebenarnya, sikap dan pemikiran semacam itu, sudah
dimulai juga oleh Muhammad Abduh atau Sayyid Ahmad Khan di India. Ijtihad dalam
konteks ini tidak jauh dari apa yang dikatakan Dr Muhammad M Husen. ‘’Ijtihad
dibuka untuk semua orang, baik yang memenuhi syarat atau tidak, yang bermental
wara’ atau yang penganut nafsu”. Gerakan ini dapat disebut sebagai
“Neo-Mu’tazilah” atau mu’tazilah gaya baru.
Karena itu, sebagai generasi Aswaja
disamping kita harus banyak mensosialisasikan pemahaman Aswaja secara utuh pada
masyaraka, tampaknya pengembangan pemahaman yang lebih luas tentang Aswaja
sangat terasa kebutuhannya, agar Aswaja tidak menjadi doktrin yang baku dan
beku, tapi doktrin yang dinamis. Tanpa melakukan pengembangan itu, maka Aswaja
akan sekedar menjadi muatan doktrin yang yang tidak mempunyai relevansi sosial.
1.
Pembahasan.
Pengembangan pemahaman Aswaja agar
tidak melenceng sebagaimana yang dilakukan kelompok JIl itu bisa dilakukan
dengan mengambil nilai-nilai yang banyak terkandung dalam Trilogi Aswaja atau
dengan mengambil nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dipakai oleh Ashabul
Madzhib al-Arba’ah lalu kita berikan pemahaman secara kontekstual.
Ada lima nilai mendasar yang terkandung dalam trilogy
Aswaja:
1) Hifz al-din yang dimaknai dengan menjaga
keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan berpindah
agama;sehingga terbentuklah sikap toleransi.
2)
Hifz al-nafs., yang
dimaknai menjaga keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan – tindakan di
luar ketentuan hukum;
3)
Hifz al-aqli.,
pemeliharaan atas kecerdasan akal;
4)
Hifz al-nasl, keselamatan
keluarga dan keturunan;
5) Hifz al-mal., keselamatan hak milik, properti dan
profesi dari gangguan dan penggusuran di luar prosedur hukum
Lima hal mendasar tersebut
dikenal dengan istilah, “Adharuriyat al-khamsah” (lima hal dasar yang
dilindungi agama),penulis sangat setuju dengan kontekstualisasi dharuriyat
al-khamsah yang dilakukan Gusdur dalam buku beliau yang berjudul
“Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai
Indonesia & Transformasi Kebudayaan”
Satu hal yang sangat khas dari
keseluruhan pemikiran Gus Dur yang tercermin dalam buku ini adalah penggunaan
khazanah Islam yang hidup dan tumbuh di pesantren sebagai pisau analisis dan
perspektif. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan Gus Dur menguasai khazanah
Islam klasik. Hal inilah yang menyebabkan Gus Dur tetap menjadi muslim yang
otentik meskipun ia bergelut dengan berbagai isu modern. Gus Dur juga tidak
terlarut dengan modernitas, meskipun sehari-hari Gus Dur bergelut dengan
modernitas.
Titik tolak pemikiran Gus Dur bukan
dengan mengagungkan modernisme, tapi mengkritik modernisme yang diuniversalkan
dengan menggunakan pisau tradisionalisme Islam. Dalam konteks ini, ungkapan
John L Esposito dan John O Voll dalam buku Makers Contemporary Islam
(2001), Gus Dur adalah seorang pembaru modern tapi bukan modernis. sangat
tepat. Kalimat tersebut bukan sekedar menggambarkan afiliasi kultural dan asal
usul sosial Gus Dur, tapi juga menggambarkan corak dan tradisi pemikirannya
yang tetap setia dengan tradisi pemikiran Islam pesantren.
Gaya pemikiran seperti ini tampak jelas
ketika Gus Dur menjelaskan soal universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban
Islam, sebuah tema yang kemudian dijadikan judul buku ini. Dalam persoalan
universalisme Islam misalnya, Gus Dur tidak perlu merujuk secara langsung
kepada al-Qurân atau hadis, sebagaimana sering dipergunakan kelompok Islam
modernis, tapi merujuk pada teori dalam ushul al-fiqh yang disebut “Adharuriyat
al-khamsah” (lima hal dasar yang dilindungi agama)
Dari penjelasan itu sebenarnya Gus Dur
sudah mempergunakan terma Islam klasik kemudian diberi makna kontekstualnya.
Terma hifz al-din misalnya, semula sekedar diberi makna memelihara
agama, dalam arti orang Islam tidak boleh keluar dari Islam dan memeluk agama
lain. Tapi di tangan Gus Dur, terma ini menjadi spirit untuk melakukan
pembelaan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Demikian juga dengan terma hifz
al-aqli, yang dalam fiqih klasik selalu dicontohkan dengan larangan meminum
minuma keras, tapi di tangan Gus Dur hifz al-aqli dikaitkan dengan
keharusan untuk memelihara dan mengasah kecerdasan. Dengan demikian, bagi Gus
Dur, universalisme Islam itu tercermin tercermin dalam ajaran-ajarannya yang
mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dibuktikan dengan
memberi perlindungan kepada masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan.
Karena itu, pemerintah harus menciptakan sebuah sistem pendidikan yang benar,
ruang untuk memperoleh informasi dibuka lebar.
Apa yang dilakukan Gus dur semacam itu
didasarkan teori klasik yakni Maslahah Mursalah yang mengacu pada Maqosid
al-Sari’ah (Adharuriyat al-khamsah) Menurut penulis masih banyak lagi
teori-teori atau prinsip-prinsip yang dipakai Ashabul al-Madzhib al-Arba’ah
dalam mencetuskan sebuah hukum seperti istihsan, maslahah mursalah, istishhab,
sadd al-dzari’ah, madzhab sahabat, syar’u man qoblana.
1.
Istihsan.
Istihsan ialah meninggalkan qiyas yang jelas
dan mengamalkan qiyas yang lebih samar karena terdapat dalil yang
menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Menurut
al-Zuhaili, Istihsan pada intinya mencakup dua bentuk yaitu menguatkan qiyas khafi
(tidak jelas) atas qiyas jali (jelas) didasarkan atas suatu dalil dan
mengecualikan masalah juz’i (parsial) dari kaidah umum didasarkan atas
suatu dalil yang lebih khusus.
Contoh istihsan
ini adalah diperbolehkanya akad salam. Sebagaimana diketahui bahwa
menurut dalil umum bahwa jual beli dengan cara demikian tidak sah karena
melakukan transaksi atas sesuatu yang belum jelas berdasarkan larangan dari
Rasulullah. Akan tetapi hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan khusus dari
Rasul yang menyatakan:
من أسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل
معلوم
Contoh yang lain adalah diperbolehnya khiyar syarat
sampai tiga hari yang menyalahi ketentuan hukum asal dalam masalah transaksi
yang mengharuskan tetapnya transaksi tersebut setelah akad disepakati
berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban bin Munqidz.
Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah
menjadikan istihsan sebagai dalil hukum. Akan tetapi, di antara mereka
terjadi perbedaan dalam volume penerapannya. Ulama Hanafiyah termasuk ulama
yang lebih banyak porsinya dalam menerapkan metode ini.
Sebaliknya, ulama Syafi’iyah, Zhahiriyah, Syi’ah dan
Mu’tazilah menolak istihsan sebagai dalil. Al-Syafi’i pernah menyatakan,
“Siapa saja yang menggunakan istihsan, ia telah membuat syari’at”.
Sementara itu, Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah memandang bahwa penggunaan
istihsan sebagai sesuatu yang mengikuti hawa nafsu dan membawa pada kesesatan
Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah
menjadikan istihsan sebagai dalil hukum..
Sebaliknya, ulama Syafi’iyah, Zhahiriyah, Syi’ah dan
Mu’tazilah menolak istihsan sebagai dalil. Al-Syafi’i pernah menyatakan,
“Siapa saja yang menggunakan istihsan, ia telah membuat syari’at”.
Sementara itu, Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah memandang bahwa penggunaan
istihsan sebagai sesuatu yang mengikuti hawa nafsu dan membawa pada kesesatan.
2.
Maslahah
Mursalah
Secara rinci dapat dikemukakan bahwa maslahah mursalah
merupakan suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan atas suatu kemaslahatan,
yang tercantum dalam Maqosid al- Syar’iah(prinsip-prinsip dasar syariat yang
lima) hal ini dilakukan ulama’ karna tidak ada rujukan yang jelas dari
nash, ijma’ dan qias namun juga tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas,
Istilah Maslahah Mursalah ini digunakan dalam ilmu ushul fiqih dengan berbagai
macam istilah, di antaranya al-istidlal, al-munasib al-mursal, al-istislah
dan al-istidlal al-mursal. Sekalipun menggunakan istilah yang berbeda, akan
tetapi maksud dan tujuannya secara umum sama.
Contoh maslahah mursalah ini adalah kebijakan pembukuan
al-Qur’an dan Hadis yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin ‘Affan dan
Umar bin Abdul Aziz, padahal hal ini tidak diperintah oleh Rasul.
Ulama yang mendukung teori ini adalah kelompok madzhab
Maliki, Hanafi dan Hanbali. Sedangkan yang melarang penggunaan teori ini
sebagai dasar penetapan hukum adalah ulama-ulama dari madzhab Syafi’i, Syi’ah
dan Dzohiri.
Gambaran di atas adalah pandangan ulama
secara garis besara, namun secara lebih terperinci, di antara para ulama
terjadi perbedaan pandangan mengenai status hukum mashlahah mursalah.
Secara garis besar pandangan-pandangan itu terbagi menjadi empat bagian sebagai
berikut:
a) Ulama yang tidak memakai istishlah secara mutlak.
Ulama yang tidak memakai istishlah secara mutlak, di antaranya, adalah ulama
dari Madzhab Hanafi yang lebih memilih al-Istihsan daripada al-Istishlah
ini. Imam al-Syafi’i tidak menyatakan secara jelas penolakannya. Beliau hanya
menegaskan bahwa apa saja yang tidak mempunyai rujukan nash tidak dapat
diterima sebagai dalil hukum.
b)
Ulama yang
menerapkan istishlah secara mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip
Rusli, berkata, “Jika seorang peneliti merasa musykil tentang hukum sesuatu,
apakah ia haram atau mubah, maka perhatikanlah mafsadat atau maslahatnya”. Menurut
ulama dari Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali, istishlah merupakan
deduksi logis terhadap sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang
berlaku dalam qiyas. Konsep ini kemudian dikembangkan secara liberal oleh
Najmuddin al-Thufi (w. 716 H). Menurutnya, inti segenap ajaran Islam yang
dikandung oleh nash adalah kemaslahatan manusia. Karena itu, segala bentuk
kemaslahatan disyari’atkan dan kemaslahatan tersebut tidak perlu didukung oleh
nash atau kandungannya.
c)
Ulama yang
membolehkan memakai istishlah sebagai dalil. Kelompok ketiga ini
menetapkan persyaratan, bahwa istishlah boleh dijadikan sebagai dalil
jika mula’imah (sesuai) dengan ashl al-kulli (prinsip umum) dan ashl
al-juz’i (prinsip parsial) dari prinsip-prinsip syariat.
d)
Ulama yang
menerima istishlah dengan tiga persyaratan yaitu: terdapat kesesuaian maslahah
dengan maksud syara’ dan tidak bertentangan dengan dalil yang qath’i, maslahah
tersebut dapat diterima oleh akal sehat serta maslahah bersifat dharuri,
yakni untuk memelihara salah satu dari: agama, akal, keturunan, kehormatan, dan
harta benda. Di antara ulama yang menetapkan tiga persyaratan diterimanya
Istishlah adalah al-Ghazali.
3.
Istishhab
Secara bahasa istishhab berarti persahabatan dan
kelanggengan persahabatan. Sedangkan menurut istilah para ulama, istishhab
adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga
adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu. Sebagaian
ulama menyatakan bahwa istishhab adalah menetapkan hukum yang ditetapkan
pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang
menunjukkan adanya perubahan.
Karena itu, jika mujtahid berhadapan dengan pertanyaan
mengenai kontrak atau pemeliharaan yang tidak ditemukan nash-nash dalam
al-Qur’an dan sunnah atau tidak ada dalil syara’ yang mutlak hukumnya, maka
kontrak (ijarah) atau pemeliharaan itu hukumnya dibolehkan berdasarkan
kaidah:
الاصل في الاشياء
الاباحة
Artinya: “Asal sesuatu itu adalah boleh (mubah)”.
Dengan demikian, jika tidak terdapat dalil yang
menunjukkan adanya perubahan, maka sesuatu itu hukumnya boleh (mubah) sesuai
dengan sifat kebolehan asalnya.
Istishhab terbagi kepada
empat macam yaitu:
a. Istishhab al-Bara’ah al-Ashliyyah (kebebasan
dasar). Ibn al-Qoyyim menyebutnya dengan istilah al-Bara’ah al-‘Adam
al-Ashliyyah. Contohnya, kita bebas dari kewajiban-kewajiban (taklif)
syar’i sampai ada dalil yang menunjukkan adanya taklif. Seorang anak kecil
terbebas dari taklif sampai ia mencapai usia baligh.
b.
Istishhab yang diakui
eksistensinya oleh syara’ dan akal. Seperti istishhab mengenai
pertanggung-jawaban utang sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa utang itu
telah dibayar atau dibebaskan.
c. Istishhab hukum, yaitu apabila dalam suatu kasus
sudah ada ketentuan hukumnya, baik mubah atau haram. Ketentuan itu terus
berlaku sampai ada dalil yang mengharamkan perkara mubah dan memperbolehkan
perkara haram. Sebab hukum asal segala sesuatu adalah mubah selain urusan harta
dan kehormatan. Berdasarkan ayat al-Qur’an:
Artinya:
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha
mengetahui segala sesuatu”.(QS 2: 29)
d. Istishhab sifat, seperti sifat hidup bagi orang
yang hilang. Sifat ini dianggap masih tetap melekat pada orang hilang sampai
ada indikator atas kematiannya. Contoh lainnya adalah sifat suci bagi air.
Sifat ini tetap melekat hingga ada tanda-tanda atas kenajisannya, baik berubah
warnanya, baunya atau rasanya.
Istishhab diterima
sebagai sumber hukum bisa dilihat dari segi syara’ atau akal. Dari segi syara’,
ternyata berdasarkan istiqra (penelitian) terhadap hukum-hukum syara’
disimpulkan bahwa hukum-hukum itu tetap berlaku sesuai dengan dalil yang ada
sampai ada dalil yang mengubahnya. Anggur yang memabukkan, berdasarkan
ketetapan dari syara’ adalah minuman haram kecuali apabila telah berubah
sifatnya (memabukan), baik dengan dicampur air atau berubah dengan sendirinya
menjadi cuka (badek).
Sebenarnya, apabila ditinjau dari segi logika, akal sehat
dengan mudah dapat menerima dan mendukung penggunaan istishhab sebagai
dasar penetapan hukum. Di sini dapat dikemukakan beberapa contoh:
a.
Tidak seorang
pun yang berhak menuduh bahwa si fulan halal darahnya lantaran murtad, kecuali
apabila ada dalil yang menunjukkan atas kemurtadannya. Sebab menurut hukum
asal, setiap orang haram darahnya. Hal ini sesuai dengan azas praduga tidak
bersalah.
b.
Seorang yang
adil tidak boleh dituduh fasik, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan
kefasikannya, karena sifat adil jika terdapat pada diri seseorang, ia menjadi
sifatnya yang melekat pada jati dirinya sampai orang yang bersangkutan
berperilaku dengan sifat yang berlawanan, yaitu sifat fasik.
c.
Apabila
seseorang diketahui masih hidup, ia tidak bisa dianggap telah meninggal kecuali
apabila ada bukti yang menunjukkan kematiannya.
Ulama yang mendukung teori istishhab ini adalah
kalangan jumhur antara lain: jumhur Maliki, Syafi’i, Hanabilah, Dzohiriyah dan
Syi’ah. Menurut mereka, istishhab bisa digunakan sebagai dalil secara
mutlak guna menetapkan hukum yang telah ada sampai ada dalil baru yang dapat
mengubahnya. Mereka yang mendukung istishhab sebagai dasar penetapan hukum
membangun argumentasinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya,
baik oleh nash atau kajian ijtihadi secara logika tetap berlaku sebelum
ada yang mengubahnya, karena hukum tidak boleh vakum.
Sedangkan menurut ulama dari kalangan Hanafiah
berpendapat bahwa istishhab ini sekedar untuk alasan menolak sesuatu yang
belum jelas. Untuk itu penggunaan istishhab ini hanya bila diperlukan
saja.
4.
Sadd
al-Dzari’ah.
Sadd al-Dzari’ah (menutup
sarana). Yang dimaksud dengan al-dzari’ah dalam ushul fiqh ialah sesuatu
yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Jika terdapat
sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan, maka sarana tersebut harus
ditutup atau dicegah. Inilah yang disebut dengan sadd al-dzari’ah.
Sedangkan kebalikannya adalah fath al-dzari’ah, yakni membuka berbagai
sarana yang mendekatkan kepada sesuatu yang halal dan membawa kepada
kemaslahatan. Menurut al-Syaukani dzari’at adalah sesuatu yang secara
lahiriah hukumnya boleh, namun akan membawa kepada perbuatan yang dilarang.
Kelihatannya metode ini lebih bersifat preventif. Artinya
segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan haram maka
hukumnya menjadi haram pula. Contoh kasus yang menggunakan metode ini adalah
larangan pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah
dari para pihak yang sedang berperkara, sebelum perkara itu memiliki kekuatan
hukum tetap. Hal ini mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidakadilan
dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya,
menerima atau memberi hadiah hukumnya boleh, akan tetapi dengan pertimbangan di
atas, dalam kasus ini harus dilarang. Contoh yang lain adalah larangan meminum
seteguk minuman yang memabukkan (padahal kalau hanya seteguk tidak memabukkan)
untuk mengantisipasi meminum dalam jumlah yang banyak.
Imam Malik dan Imam Ahmad menempatkan sadd al-dzari’ah
sebagai salah satu dalil hukum. Sedangkan Imam al-Syafi’i, Imam Abu Hanifah,
dan Madzhab Syi’ah menerapkannya pada kondisi-kondisi tertentu. Adapun Madzhab
Zhahiri menolaknya secara tegas dan totaliter.
5.
Syar’u Man
Qablana.
Syar’u man qablana adalah syariat umat sebelum Islam yang
dibawa oleh Rasulullah Saw. Para ulama Ushul Fiqh mengkaji syariat sebelum
Islam dalam kaitannya dengan penerapan syariat tersebut bagi umat Islam. Dalam
perkara ini, ada bagian-bagian dari syariat sebelum Islam yang telah dibatalkan
oleh syariat Islam, baik diiringi dengan dalil yang sharih maupun tidak
diiringi dengan dalil yang sharih tetapi menunjukkan dalil lain yang sifatnya
berbeda. Misalnya, taubat zaman Nabi Musa as dengan cara bunuh diri dan tidak
akan diperoleh satu keterangan pun yang melegalkan cara taubat seperti ini bagi
umat Nabi Muhammad Saw.
Di samping itu, ada juga syariat yang masih tetap diberlakukan
dan disertai dengan dalil, seperti ibadah puasa sebagaimana disebutkan
dalam al-Qur’an:
Artinya: “Hai
orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.(QS. 2: 183)
Dalam hal syari’at yang diiringi dengan dalil, baik
penetapannya maupun perubahannya, para ulama tidak merasa kesulitan dalam
memutuskan penerapannya bagi umat Islam dan sepakat bahwa hal ini bisa
dijadikan dalil. Akan tetapi, syariat yang tidak diiringi dengan suatu dalil
menjadi persoalan pelik di kalangan para ulama. Di antara mereka terjadi
perbedaan pendapat. Seperti yang terdapat dalam al-Qur’an:
Artinya: “Oleh
Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa
yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain,
atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah
membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.(QS.
5: 32)
Menurut jumhur ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki,
sebagian ulama Madzhab al-Syafi’i dan salah satu pendapat Imam Ahmad, syari’at
umat sebelum Islam masih tetap berlaku. Di sisi lain, Madzhab Asy’ari,
Mu’tazilah, Syiah, yang kuat dalam Madzhab al-Syafi’i, salah satu riwayat dari
Imam Ahmad, Imam al-Ghazali, al-Amidi,
al-Razi, dan Ibnu Hazm menetapkan bahwa syariat sebelum Islam tidak dapat
diberlakukan bagi umat Islam sehingga ada dalil yang menegaskannya.
6.
Kesimpulan
Dari percikan pemikiran di atas kiranya
dapat dipahami pentingnya menjadikan aswaja sebagai Manhajul fikr dengan
menggali nilai nilai yang terkandung dalam trilogy aswaja agar bisa menjawab
realiatas yang terjadi di masyarakat.
50
AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH
Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah
terdiri dari 50 aqidah, di mana
yang 50 aqidah ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu:
1. Aqidah Ilahiyyah (عقيدة الهية) dan
2. Aqidah Nubuwwiyah (عقيدة نبوية)
1. Aqidah Ilahiyyah (عقيدة الهية) dan
2. Aqidah Nubuwwiyah (عقيدة نبوية)
Adapun Aqidah Ilahiyyah terdiri dari
41 sifat, yaitu:
a. 20 sifat yang wajib bagi Allah
swt: wujud (وجود), qidam (قدم), baqa (بقاء),
mukhalafah lil hawaditsi (مخالفة للحوادث), qiyamuhu bin
nafsi (قيامه بالنفس), wahdaniyyat (وحدانية),
qudrat (قدرة), iradat (ارادة), ilmu (علم),
hayat (حياة), sama’ (سمع), bashar (بصر),
kalam (كلام), kaunuhu qadiran (كونه قديرا),
kaunuhu muridan (كونه
مريدا), kaunuhu ‘aliman (كونه عليما),
kaunuhu hayyan (كونه
حيا), kaunuhu sami’an (كونه سميعا),
kaunuhu bashiran (كونه
بصيرا), dan kaunuhu mutakalliman (كونه متكلما).
b. 20 sifat yang mustahil bagi Allah swt: ‘adam (tidak ada), huduts (baru), fana’ (rusak), mumatsalah lil hawaditsi (menyerupai makhluk), ‘adamul qiyam bin nafsi (tidak berdiri sendiri), ta’addud (berbilang), ‘ajzu (lemah atau tidak mampu), karohah (terpaksa), jahlun (bodoh), maut, shamam (tuli), ‘ama (buta), bukmun (gagu), kaunuhu ‘ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan (كونه جاهلا), kaunuhu mayyitan (كونه ميتا), kaunuhu ashamma (كونه أصم), kaunuhu a’ma (كونه أعمى), dan kaunuhu abkam (كونه أبكم).
b. 20 sifat yang mustahil bagi Allah swt: ‘adam (tidak ada), huduts (baru), fana’ (rusak), mumatsalah lil hawaditsi (menyerupai makhluk), ‘adamul qiyam bin nafsi (tidak berdiri sendiri), ta’addud (berbilang), ‘ajzu (lemah atau tidak mampu), karohah (terpaksa), jahlun (bodoh), maut, shamam (tuli), ‘ama (buta), bukmun (gagu), kaunuhu ‘ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan (كونه جاهلا), kaunuhu mayyitan (كونه ميتا), kaunuhu ashamma (كونه أصم), kaunuhu a’ma (كونه أعمى), dan kaunuhu abkam (كونه أبكم).
c. 1 sifat yang ja’iz bagi Allah
swt.
Aqidah
Nubuwwiyah terdiri dari 9 sifat, yaitu:
a. 4 sifat yang wajib bagi para
Nabi dan Rasul: siddiq (benar), tabligh (menyampaikan), Amanah, dan
fathanah (cerdas).
b. 4 sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul: kidzib (bohong), kitman (menyembunyikan), khianat, dan baladah (bodoh).
c. 1 sifat yang ja’iz bagi para Nabi dan Rasul.
b. 4 sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul: kidzib (bohong), kitman (menyembunyikan), khianat, dan baladah (bodoh).
c. 1 sifat yang ja’iz bagi para Nabi dan Rasul.














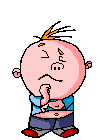

0 komentar:
Posting Komentar
Mohon Saran dan Kritiknya